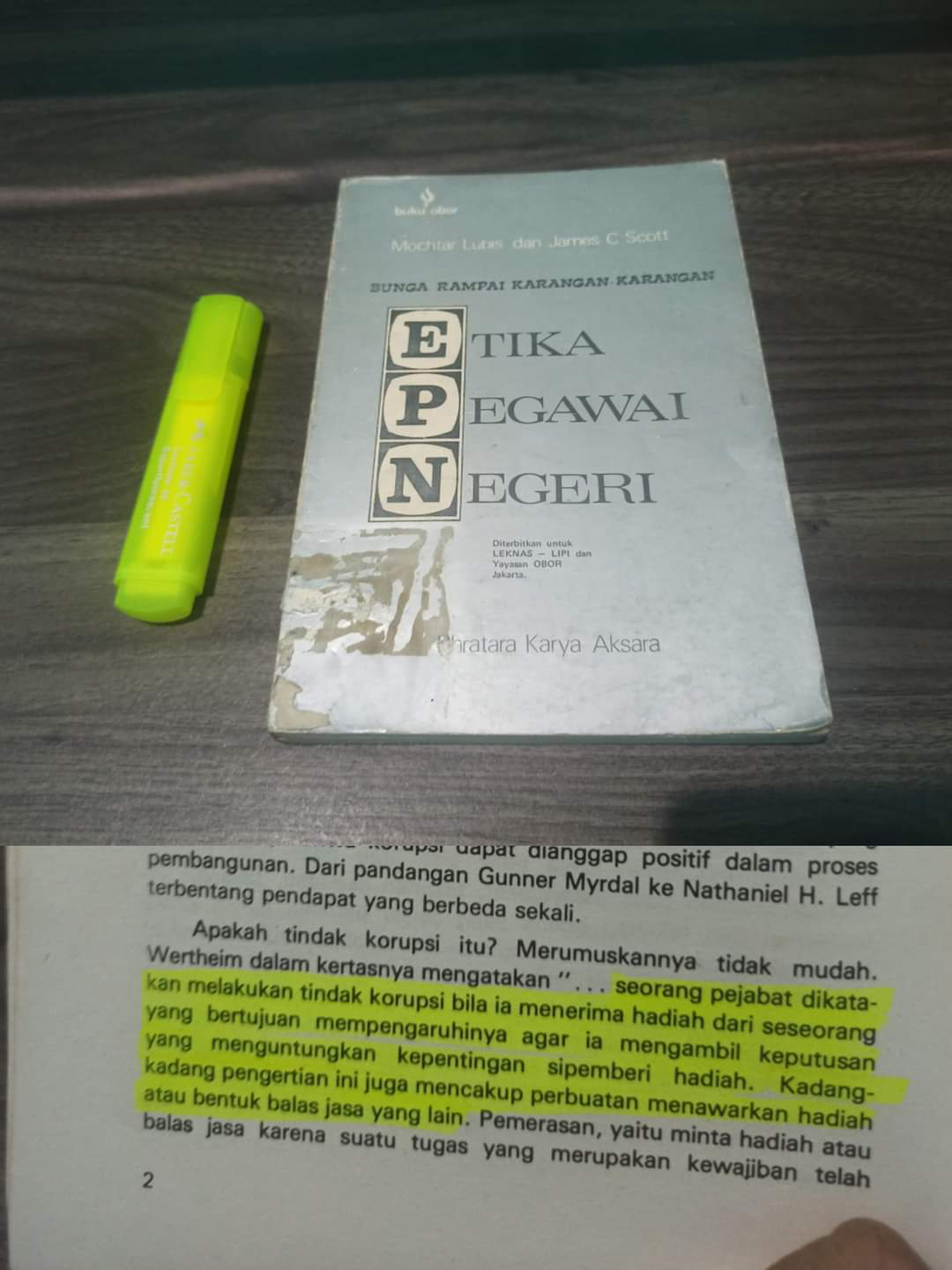Saya baru saja mengkhatamkan buku "Berebut Iman di Tanah Sunan, Islamisasi dan Kristenisasi di Surakarta Masa Kolonial hingga Awal Reformasi". (Saya tidak menyangka ulasannya akan menjadi panjang, makanya saya buat menjadi dua bagian, agar pembaca tidak mabuk tulisan).
Dalam buku ini, Adif Fahrizal Arifyadiputra melukiskan secara kronologis berlangsungnya kontestasi antara Islam dengan Islamisasinya (dakwah) vis a vis Kristen dengan Kristenisasinya (misi, evangelization, atau penginjilan) di Surakarta. Istilah untuk kompetisi kedua agama, yang penulis gunakan dalam bukunya ini: proselitisasi --sebuah lema yang belum masuk dalam KBBI kita.
***
Mari kita ulas secara kronologis. Sampai akhir abad ke-19, hampir tidak ada penduduk pribumi Surakarta yang memeluk agama Kristen, atau selain Islam. Sebab Surakarta termasuk daerah Vorstenlanden, yang wilayahnya berada di bawah penguasaan raja.
Mengutip dari bukunya Kuntowijoyo, Adif menulis: "Baik sunan Surakarta maupun adipati Mangkunegaran, keduanya dipandang bukan hanya sebagai pemimpin politik tapi juga kepala agama Islam. Dalam pandangan pemerintah kolonial, memperbolehkan penyebaran Kristen di daerah kekuasaan pribumi yang penguasanya adalah pemimpin politik sekaligus kepala agama Islam hanya akan menimbulkan masalah belaka. Walaupun demikian, sunan secara pribadi sesungguhnya tidak berkeberatan dengan aktivitas zending dan tidak memusuhi agama Kristen. Hanya saja, sebagai panatagama, sunan berkeberatan jika rakyatnya memeluk agama di luar Islam." (Hlm. 29)
Jadi, memang ada larangan dari pemerintah kolonial untuk perkabaran injil di Surakarta. Bahkan permohonan izin untuk pendirian rumah sakit zending pada 1891 juga ditolak oleh pemerintah. Namun demikian, lewat kebaktian keluarga, seorang dokter zending, dr. J.G. Scheurer, berhasil menarik minat beberapa orang Jawa yang diundangnya untuk menjadi Kristen. Akibat tindakannya ini, sang dokter terpaksa harus meninggalkan Surakarta. (Hlm. 28-29).
Adanya larangan tidak menghalangi usaha perkabaran Injil di Surakarta. Larangan tersebut baru dicabut pada 1910, setahun setelah A.W.F Idenburg dilantik menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru, menggantikan JB. Van Heutsz. Sejak saat itu, aktivitas zending dimulai dengan penyediaan layanan pendidikan berupa sekolah.
Beberapa tahun kemudian, persaingan semakin kompetitif. Katolik mulai masuk ke Surakarta pada 1918 ditandai dengan berdirinya Gereja Santo Antonius di Purbayan. Tiga tahun kemudian, HIS (Hollandsch-Inlandsche School) Katolik berdiri. Pada tahun yang sama HIS Kanisius didirikan di Sosronegaran. Nama sekolah yang terkahir ini di tahun berikutnya semakin intensif membuka cabang baru di berbagai penjuru Surakarta. Inilah sekolah yang mendapat subsidi dan kemudahan dari pemerintah kolonial yang mana pada mulanya netral agama. Banyak di antara kaum priyayi yang menyekolahkan anaknya ke sekolah Katolik, tak terkecuali putri Sunan Paku Buwono X. (Hlm. 31-33)
Hanya dalam waktu delapan tahun sejak larangan dicabut, total pemeluk Kristen di Solo maju pesat. Pada 1918 warga jemaat Gereformeerd di Solo sudah berjumlah 228 orang yang meliputi etnis Jawa dan Tionghoa. (Hlm.31)
Sampai di sini sebenarnya bisa dimengerti --yang dalam buku ini juga ada bab khusus yang membahasnya-- latar belakang berdirinya Muhammadiyah (1912) yang tujuan utamanya adalah untuk membendung arus (meminjam isitilah dari judul buku Alwi Shihab) Kristenisasi secara elegan, yakni dengan mendirikan layanan yang sama berbasis Islam.
***
Zaman kolonialisme Jepang, meskipun hanya berlangsung singkat, adalah masa yang paling sulit buat umat Kristen di Indonesia, karena pada masa ini banyak pekerja zending yang berkebangsaan Belanda ditahan oleh Jepang. Mereka yang dianggap kaki tangan Belanda meliputi orang-orang Indo, Cina, dan Kristen pribumi. (Hlm. 35-36).
Sementara itu, hambatan Islamisasi tidak sesulit yang dialami oleh pihak Kristen. Bahkan beberapa tokoh Islam --Seperti Buya Hamka dan Wahid Hasyim-- dapat memanfaatkan kesempatan dari Jepang untuk mengorganisir umat Islam. Sayangnya kronik tersebut tidak dielaborasi dalam buku ini.
***
Di masa Revolusi, sekolah-sekolah Kanisius, meskipun dalam kondisi sulit, tetap mampu berkembang dengan baik. Sekolah-sekolah ini dapat menunjukkan efektivitasnya sebagai sarana perkabaran Injil. Bahkan terjadi peningkatan jumlah murid dari 9.726 orang (163 dibaptis) pada 1945 menjadi 12.349 (675 dibaptis) orang pada 1950. Pada masa kemerdekaan ini pula ada seorang tentara yang menjadi Katolik dan belakangan ditahbiskan sebagai pahlawan Solo, yaitu Letkol Ignatius Slamet Riyadi. (Hlm. 37).
Slamet Riyadi diabadikan menjadi nama jalan utama di kota Solo. Di ujung jalan protokol tersebut terdapat patung besarnya sambil memegang senjata yang diarahkan ke langit. Ia dikenang karena berhasil mengusir NICA dan tentara Belanda serta berhasil menduduki kota Solo selama empat hari dari tanggal 7-10 Agustus 1949.
***
Perang kemerdekaan berakhir. Babak baru dekolonisasi Indonesia dimulai. Banyak petugas misi dari Belanda yang memutuskan menjadi warga negara Indonesia. Kesempatan itu dibuka pada tahun 1949-1951.
Namun demikian, situasi politik paska kolonial yang masih diwarnai sentimen anti-Belanda mencegah banyak sekali tenaga misi Katolik (90% adalah orang Belanda) untuk berkarya di Indonesia. Pada 1952, Kementrian Agama menolak menolak memberikan rekomendasi bagi 500 orang misionaris Katolik berkebangsaan Belanda. Malah pada 1 Agustus 1959, pemerintah melarang pengajar dari luar negeri mengajar di sekolah-sekolah Indonesia. (Hlm. 38)
***
Ada kejutan besar pada masa Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Surakarta, yang menjadi lahan subur tempat proselitisasi itu, ternyata sekaligus menjadi kota dengan basis massa PKI terbesar tiada tandingnya.
Berikut laporan hasil Pemilu 1955 di Surakarta yang dikumpulkan oleh Mulyadi dan Soedarmono: NU hanya memperoleh 1.998 suara (1,61%) dari total jumlah suara sah; Masyumi 13.733 suara (11, 1%); PNI 37.144 suara (30%); dan PKI 70.808 suara (57, 26%). (Hlm. 26)
Dengan dibubarkannya Masyumi, praktis tinggal NU partai Islam saat itu yang menjadi hambatan buat PKI. Data di atas menjadi penting untuk kita ingat. Sebab paska G30S, mereka yang menjadi massa PKI dan penganut agama secara nominal (baca: abangan), menjadi sasaran empuk untuk diganyang oleh rezim yang akan berkuasa selanjutnya.
Siapa yang menyangka, konflik antara komunitas muslim (baca: santri) versus abangan --eks PKI, atau yang sekadar dituduh PKI-- inilah yang menjadi sebab perubahan besar arus proselitisasi di masa awal Orde Baru.
***
Imbas dari peristiwa Gestapu (istilah terinspirasi dari nama Gestapo yang ada di Jerman) tidak sekadar mengubah konstelasi politik, melainkan juga berdampak pada tatanan sosial-budaya (konflik horisontal antara massa pendukung PKI versus anti-PKI yang diwakili oleh kaum santri), yang kemudian mengubah arus proselitisasi. Kita fokus membahas yang terakhir.
Rezim Orde Baru berdiri, setelah sebelumnya militer AD bekerjasama dengan komunitas santri, berhasil menumpas PKI (sampai ke akar-akarnya). Banyak kader-kader PKI yang ditangkap, tak terkecuali simpatisan, termasuk pula orang-orang tak tahu menahu perkara politik (korban tertuduh PKI). Mereka semua menjadi tahanan politik (tapol).
Mengutip dari bukunya Pdt. Jan S Aritonang dan Karel A Steenbrink, A History of Christianity in Indonesia (2008), Adif menulis: "Di luar situasi yang genting tersebut, baik GKD (Gereja Kristen Djawa) maupun Gereja Katolik mendapat lahan terbuka luas bagi perkabaran Injil seiring dengan diperkenankannya indoktrinasi bagi para tahanan militer yang disangkakan terlibat PKI. Kesempatan bagi perkabaran Injil di Solo semakin dipermudah mengingat Pejabat Wali Kota Solo yang menggantikan Oetomo Ramelan (Wali Kota Solo yang berasal dari PKI) adalah Letkol Th. J. Soemantha yang seorang Katolik." (Hlm. 41)
Wawancara Adif (2015) dengan Pdt. (Emeritus) Edi Trimodoroempoko menyatakan: "Di Solo aparat mendatangkan para pemuka agama --termasuk Kristen-- untuk memberikan penerangan tentang agama pada para tahanan yang dikumpulkan di Pagelaran Keraton Kasunanan." (Hlm. 41-41)
Para tapol dari PKI atau yang di-PKI-kan ini diasumsikan sebagai orang-orang yang tidak beragama. Mereka harus kembali ke "jalan yang lurus", yaitu meninggalkan PKI, dengan cara memilih agama formal yang sudah ditetapkan dan diakui negara (Ada lima: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha).
Bisa Anda bayangkan bagaimana ketakutan psikologis massa yang dikumpulkan tersebut? Jelas ada trauma untuk memilih Islam yang diwakili oleh komunitas santri yang tidak bisa memberikan jaminan keamanan buat mereka. Maka di sinilah Kristenisasi menemukan jalan landainya.
***
Tahun 70an, setelah kondisi benar-benar stabil, barulah bermunculan data statistik. Oleh karena tidak ada catatan (termasuk dalam buku yang sedang kita bedah ini) mengenai jumlah dan persentase pemeluk Kristen tahun 60an di Surakarta, maka komparasinya adalah dengan data dua dekade sebelumnya.
Menurut catatan Kantor Urusan Agama Kota Besar Surakarta tahun 1951, jumlah penganut Kristen (Protestan dan Katolik) di kota tersebut hanya mencakup 4% dari keseluruhan jumlah penduduk Surakarta. Dua dekade kemudian (1970) angkanya naik hampir sembilan kali lipat, yakni 17,59%, alias jumlahnya mencapai 78.991 orang. (Hlm. 128).
Namun demikian, sejauh mana gelombang konversi massal paska-1965 terjadi sebagai hasil perkabaran Injil sulit untuk dipastikan. Konversi yang terjadi tidak bisa dilihat sebagai prakarsa gereja semata, sebab ada pula peran negara demi meneguhkan kepentingan politiknya.
***
Kita memasuki era 80-90an. Terjadinya konversi juga tentu ikut mempengaruhi dinamika perimbangan jumlah penduduk Islam dan Kristen di Surakarta. Pada 1980 jumlah penduduk Kristen (Katolik & Protestan) naik menjadi 112.257 orang. Sebaliknya pada tahun yang sama jumlah Muslim naik menjadi 336.084 orang, yang pada dekade sebelumnya (1970) sebanyak 286.928 jiwa. (Hlm.144).
Data di atas berkorelasi dengan meningkatnya jumlah rumah ibadah. Jika pada 1969 jumlah masjid hanya 71 (sempat menurun jadi 69 pada 1970), pada 1982 meningkat menjadi 152. Sementara gereja di tahun yang sama semula hanya 29 naik menjadi 84 --peningkatan yang sangat signifikan. (Hlm.147).
Tahun 80-90an adalah dekade puncak kekuasaan Orde Baru. Pembangunan --sebagai tanda modernitas-- semakin intensif. Dan salah satu penanda modernitas adalah sekolah.
Pembangunan sekolah untuk memberantas buta huruf menjadi hal yang sangat penting. Di samping pemerintah, lembaga-lembaga swasta yang bercorak agama juga turut berperan dalam menyediakan layanan pendidikan. Di lapangan ini, tak ketinggalan baik Islam maupun Kristen berlomba untuk membuka institusi pendidikan formal.
Yang menarik di era ini adalah saat terjadi arus balik proselitisasi, yakni mereka yang kembali memeluk Islam setelah sempat ikut konversi menjadi Kristen. Catatan dari Kuntowijoyo, mereka meninggalkan Islam disebabkan oleh dendam politik, bukan karena kerelaan spiritual. Tetapi, karena tema ini tidak dielaborasi dalam buku ini, makanya tidak perlu kita bahas. Saya merekomendasikan buku berjudul "Misi Kristen versus Dakwah Islam di Indonesia" karya Arif Wibowo --sebagai pelengkap buku yang sedang kita ulas ini.
***
Orde Baru tumbang, berganti Reformasi. Lagi-lagi kita menghadapi krisis multidimensi. Konflik horisontal terjadi di banyak tempat, seperti di Poso, Sampit, dan Ambon. Apa yang terjadi di Ambon tak dipungkiri turut berdampak pula terhadap kerukunan beragama yang terjadi berbagai daerah, tak terkecuali di Solo. Di buku ini dibahas lengkap ekses-ekses akibat konflik tersebut. Saya tidak akan mengulas semuanya, silakan baca sendiri bukunya.
Catatan menarik dari Adif: "Berakhirnya era Orde Baru membuka ruang bagi menguatnya sentimen-sentimen agama yang sebelumnya hanya dipendam di bawah permukaan, dan kemunculan kelompok-kelompok agama yang membawakan identitas keberagamaannya dengan lebih tegas. Kelompok-kelompok tersebut memang bukan kelompok yang dominan tapi kelahiran mereka sedikit-banyak adalah hasil dari proses pengagamaan pada masa Orde Baru. Di sinilah letak paradoksnya, yakni di satu sisi pemerintah Orde Baru menabukan penonjolan identitas primordial, namun di sisi lain proses pengagamaan yang mereka dukung sesungguhnya ikut menaburkan benih bagi munculnya kelompok-kelompok tersebut. Kemunculan mereka pada akhirnya hanya soal momentum belaka, dan momentum itu datang ketika." (Hlm.194-195).
***
Demikianlah ulasan untuk tesis yang kemudian dibukukan ini, ada tiga kutipan dari Adif yang perlu saya tulis ulang di sini:
"Perlu pula diingat bahwa pesatnya pertumbuhan rumah ibadah secara kuantitatif belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas keberagaman --suatu hal yang sulit diukur. Namun, yang jelas, data-data kuantitatif di atas bisa menjadi indikasi bahwa proses pengagamaan berlangsung dengan sangat intensif di Surakarta." (Hlm. 150).
"Ditinjau dari dampaknya, sudah tentu Islamisasi maupun Kristenisasi mendorong tumbuhnya identitas keberagamaan dalam masyarakat Indonesia. Adalah sebuah hal yang menarik bahwa pada masa Orde Baru pemerintah RI satu sisi menabukan penonjolan identitas keberagaman, namun di sisi lain pemerintah secara tidak langsung ikut berperan dalam menumbuhkan identitas keberagamaan." (Hlm.5).
"Dalam kasus Surakarta, di balik hubungan yang harmonis di permukaan, ternyata di bawah berlangsung pula persaingan dan kecurigaan. Memang persaingan itu tidak meletup menjadi konflik terbuka. Ketegangan diam-diam antara komunitas Muslim dan Kristen juga tetap diimbangi upaya membangun toleransi dan kerja sama. Akan tetapi, runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang bagi munculnya kelompok dan tindakan yang sedikit-banyak menggoyahkan harmoni hubungan antar komunitas." (Hlm. 139).
***
Terakhir, saya ingin menutup uraian ini dengan kembali ke pertanyaan yang menjadi judul ulasan saya. Apa pentingnya kita memahami proselitisasi? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membangun sikap moderat dan menumbuhkan kebijaksanaan.
Segala bentuk konflik antar komunitas agama tidak bisa dipandang sekadar dari kacamata: mayoritas menindas minoritas. Tak bisa kita merasa diri paling toleran kalau akar permasalahnya kita tidak paham.
Proselitisasi juga punya tata kramanya sendiri.[]
 02.04
02.04
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 23.53
23.53
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 01.58
01.58
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 01.53
01.53
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 21.57
21.57
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 07.15
07.15
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 20.59
20.59
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 02.36
02.36
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 07.23
07.23
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 05.47
05.47
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 09.16
09.16
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 21.55
21.55
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 01.06
01.06
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 00.38
00.38
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in
 06.40
06.40
 Rumahku Surgaku
Rumahku Surgaku
 Posted in
Posted in